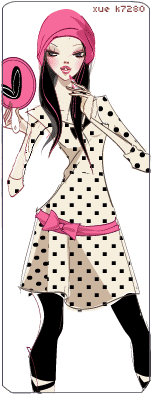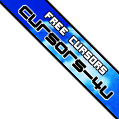BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Perawatan kesehatan adalah sebagai suatu lapangan
khusus dibidang kesehatan, keterampilan hubungan antar manusia dan
keteerampilan organisasi diterapkan dalam hubungan yang serasi kepada
keterampilan anggota profesi kesehatan lain dan kepada tenaga social demi untuk
memelihara kesehatan masyarakat (Ruth B. Freeman,1961). Komunitas dipandang
sebagai target pelayanan kesehatan yang bertujuan mencapai kesehatan komunitas
sebagai suatu peningkatan kesehatan dan kerjasama sebagai suatu mekanisme untuk
mempermudah pencapaian tujuan yang berarti masyarakat atau komunitas dilibatkan
secara aktif untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam pelaksanaan perawatan kesehatan dibutuhkan
system pelayanan kesehatan yang maksimal guna menunjang keberhasilan perawatan
kesehatan. Salah satu usaha untuk mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal
dibutuhkan usaha untuk pembangunan nasional, yang bertujuan untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan
visi pembangunan nasional melalui pembangunan kesehatan yang ingin dicapai untuk
mewujudkan Indonesia sehat 2010.
1.2
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana system pelayanan kesehatan di
Indonesia?
2.
Bagaimana konsep Indonesia sehat 2010?
3.
Apakah system kesehatan nasional (SKN)?
4.
Apakah MDGs?
1.3
Tujuan
1.3.1
Tujuan umum
Mengidentifikasi
tentang system pelayanan kesehatan di indonesia
1.3.2
Tujuan khusus
1.
Menjelaskan tentang system pelayanan
kesehatan di Indonesia
2.
Menjelaskan konsep Indonesia sehat 2010
3.
Menjelaskan system kesehatan nasional
(SKN)
4.
Menjelaskan tentang MDGs
1.4
Manfaat
1.
Mahasiswa memahami konsep system
pelayanan kesehatan sehingga menunjang pembelajaran mata kuliah.
2.
Mahasiswa mengetahui system pelayanan
kesehatan yang benar sehingga dapat menjadi bekal dalam persiapan praktik di rumah sakit
1.5
Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun atas 4 bab yang terdiri dari bab
1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa
sub pokok, bab 3 berisi pembahasan yang terdiri dari 4 poin dan yang terakhir
bab 4 yaitu penutu.
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Pelayanan Kesehatan
Bila
membahas tentang masalah system pelayanan kesehatan, ada 3 pengertian yang
terkandung didalamnya yaitu: konsep dasar system, konsep dasar kesehatan,
system pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia dikaitkan dengan
pelayanan kesehatan, peran pelayanan kesehatan dalam pengembangan sumber daya
manusia dan tantangan-tantangan pelayanan kesehatan dalam pengembangan sumber
daya manusia.
2.2 Konsep Dasar Sistem
2.2.1
Pengertian system
Pengertian system banyak macamnya. Beberapa
diantaranya yang dipandang cukup penting adalah:
1) System
adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses
atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya
menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan.
2) System
adalah suatu struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling
berhubungan yang bekerja sebagai satu unit organic untuk mencapai keluaran yang
diinginkan secara efektif dan efisien.
3) System
adalah suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang
berhubungan serta saling mempengaruhi yang dengan sadar dipersiapkan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dari pengertian diatas, maka pengertian system
secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yakni:
1) System
sebagai suatu wujud
Suatu system disebut
sebagai wujud (entity), apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun
dalam system tersebut membentuk suatu wujud yang cirri-cirinya dapat
dideskripsikan atau digambarkan dengan jelas. Tergantung dari sifat
bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk system, maka system sebagai
wujud dapat dibedakan atas dua macam:
a. System
sebagai suatu wujud yang konkrit
Dalam bentuk ini, sifat
dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk system adalah konkrit
dalam arti dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh : suatu mesin yang
bagian-bagian atau elemen-elemennya adalah berbagai unsur suku cadang
b. System
sebagai suatu wujud yang abstrak
Dalam bentuk ini, sifat
dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk system adalah abstrak
dalam arti tidak dapat ditangkap oleh panca indra. Contohnya adalah: system
kebudayaan yang bagian-bagian atau elemen-elemennya adalah berbagai unsur
budaya.
2) System
sebagai suatu metode
Suatu system disebut
sebagai suatu metode, apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun
dalam system tersebut membentuk suatu metode yang dapat dipakai sebagai alat
dalam melakukan pekerjaan administrasi. Contohnya adalah system pengawasan yang
bagian-bagian atau elemen-elemen pembentuknya adalah berbagai peraturan.
2.2.2
Ciri-ciri system
Sesuatu
disebut system, apabila ia memiliki beberapa cirri pokok system. Ciri-ciri
pokok yang dimaksud banyak macamnya, yang apabila disederhanakan dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Ciri-ciri
system menurut Elias M.Awad (1979).
1) System
bukanlah sesuatu yang berada diruang hampa, melainkan selalu berinteraksi
dengan lingkungan. Tergantung dari pengaruh interaksi dengan lingkungan
tersebut, system dapat dibedakan atas dua macam:
·
System bersifat terbuka
Dikatakan terbuka
apabila system tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada sistem
yang bersifat terbuka berbagai pengaruh yang diterima dari lingkungan dapat
dimanfaatkan oleh system untuk menyempurnakan system yang ada. Pemanfaatan
seperti ini memang memungkingkan, karena di dalam system terdapat mekanisme
penyesuaian diri, yang antara lain karena adanya unsur umpan balik (feed back)
·
System bersifat tertutup
Dikatakan tertutup
apabila system tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungannya tidak
dipengaruhi.
2) System
mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri, yang antara lain juga
disebabkan karena di dalam system terdapat umpan balik (feed back)
3) System
terbentuk dari dua atau lebih subsistem, dan setiap subsistem terdiri dari dua
atau lebih subsistem lain yang lebih kecil, demikian seterusnya.
4) Antara
satu subsistem dengan subsistem lainnya terdapat hubungan yang saling
tergantung dan saling mempengaruhi. Keluaran subsistem misalnya, menjadi
masukan bagi subsistem lain yang terdapat dalam system
5) System
mempunyai tujuan atau sasaran yang ingn dicapai. Pada dasarnya tercapai tujuan
atau sasaran ini adalah sebagai hasil kerja sama dari berbagai subsistem yang
terdapat dalam system.
b. Menurut
Shode dan Dan Voich Jr. (1974)
1) Sistem
mempunyai tujuan, karena itu semua perilaku yang ada pada system pada dasarnya
bermaksud mencapai tujuan tersebut (purposive
behavior)
2) System,
sekalipun terdiri atas berbagai bagian atau elemen, tetapi secara keseluruhan
merupakan suatu yang bulat dan utuh (wholism)
jauh melebihi kumpulan bagian atau elem tersebut.
3) Berbagai
bagian atau elemen yang terdapat dalam system saling terkait, berhubungan dan
berinteraksi.
4) System
bersifat terbuka dan selalu berinteraksi dengan system lain yang lebih luas,
yang biasanya disebut dengan lingkungan.
5) System
mempunyai kemampuan transformasi, artinya mampu mengubah sesuatu menjadi
sesuatu yang lain. Dengan kata lain, system mempu mengubah masukan menjadi
keluaran.
6) System
mempunyai mekanisme pengendalian, baik dalam rangka menyatukan berbagai bagian
atau elemen, juga dalam rangka mengubah masukan menjadi keluaran.
Dari
dua pendapat ahli tersebut tentang ciri-ciri system, pada dasarnya tidak banyak
berbeda, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dan secara sederhana, ciri-ciri
tersebut dapat dibedakan atas empat macam saja, yaitu:
1) Dalam
system terdapat bagian atau elemen yang satu sama lain saling berhubungan dan
mempengaruhi, yang kesemuanya membentuk satu kesatuan, dalam arti kesemuanya
berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama yang telah ditetapkan.
2) Fungsi
yang diperankan oleh masing-masing bagian atau elemen yang membentuk satu
kesatuan tersebut adalah dalam rangka mengubah masukan menjadi keluaran yang
direncanakan.
3) Dalam
melaksanakan fungsi tersebut, semuanya bekerja sama secara bebas namun terkait,
dalam arti terdapat mekanisme pengendalian yang mengarahkannya agar tetap
berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan.
4) Sekalipun
system merupakan satu kesatuan yang terpadu, bukan berarti ia tertutup terhadap
lingkungan.
2.3 Konsep Dasar Kesehatan
Kesehatan menurut WHO 1974 adalah suatu keadaan
sejahtera sempurna yang lengkap, ,meliputi: kesejahteraan fisik, mental dan
social. Bukan semata-mata bebas dari penyakit dan/atau kelemahan. White (1977)
sehat adalah keadaan dimana seseorang ketika diperiksa oleh ahlinya tidak
mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat
tanda-tanda penyakit atau kelainan. Sedangkan system kesehatan adalah kumpulan
dari berbagai factor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam
suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tuntutan
kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat pada setiap saat
yang dibutuhkan (WHO,1984). Untuk Negara Indonesia, pengertian system kesehatan
dikenal dengan istilah System Kesehatan Nasional (SKN), yaitu suatu tatanan
yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai
derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti
yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2.4 Sistem Pelayanan Kesehatan
Pelayanan
merupakan kegiatan dinamis berupa membantu menyiapkan, menyediakan dan
memproses, serta membantu keperluan orang lain. Pelayanan kesehatan adalah
setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga,
kelompok ataupun masyarakat.
2.4.1 Jenis
pelayanan kesehatan
Menurut
pendapat Hodgetts dan Cascio (1983), ada dua macam jenis pelayanan kesehatan.
1. Pelayanan
kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan
yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (public health services) ditandai dengan
cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi.
Tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit, dan sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.
2. Pelayanan
kedokteran
Pelayanan kesehatan
yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat
bersifat sendiri (soslo practice)
atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (institution), tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan
memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan
keluarga.
2.4.2 Syarat
pokok pelayanan kesehatan
Suatu
pelayanan kesehatan dikatakan baik apabila:
1. Tersedia
(available) dan berkesinambungan (continuous)
Artinya semua jenis
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan, serta
keberadaannya dalam masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan.
2. Dapat
diterima (acceptable) dan bersifat
wajar (appropriate)
Artinya pelayanan
kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan
masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat,
kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan mesyarakat, serta bersifat tidak wajar,
bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik.
3. Mudah
dicapai (accessible)
Ketercapaian yang
dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan
pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan
menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di
daerah perkotaan saja, dan sementara itu tidak ditemukan didaerah pedesaan,
bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.
4. Mudah
dijangkau (affordable)
Keterjangkauan yang
dimaksud adalah terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang
seperti itu harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai
dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya
mungkin dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja bukanlah kesehatan yang
baik.
5. Bermutu
(quality)
Mutu yang dimaksud
disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan, yang disatu pihak tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan
kode etik serta standart yang telah ditetapkan.
2.4.3 Prinsip
pelayanan prima di bidang kesehatan
1. Mengutamakan
pelanggan
Prosedur pelayanan
disusun demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan, bukan untuk memeperlancar
pekerjaan kita sendiri. Jika pelayanan kita memiliki pelanggan eksternal dan
internal, maka harus ada prosedur yang berbeda, dan terpisah untuk keduanya.
Jika pelayanan kita juga memiliki pelanggan tak langsung maka harus
dipersiapkan jenis-jenis layanan yang sesuai untuk keduanya dan utamakan
pelanggan tak langsung.
2. System
yang efektif
Proses pelayanan perlu
dilihat sebagai sebuah system yang nyata (hard system), yaitu tatanan yang
memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai unit dalam organisasi. Perpaduan
tersebut harus terlihat sebagai sebuah proses pelayanan yang berlangsung dengan
tertib dan lancar dimata para pelanggan.
3. Melayani
dengan hati nurani (soft system)
Dalam transaksi tatap
muka dengan pelanggan, yang diutamakan keaslian sikap dan perilaku sesuai
dengan hati nurani, perilaku yang dibuat-buat sangat mudah dikenali pelanggan
dan memperburuk citra pribadi pelayan. Keaslian perilaku hanya dapat muncul
pada pribadi yang sudah matang.
4. Perbaikan
yang berkelanjutan
Pelanggan pada dasarnya
juga belajar mengenali kebutuhan dirinya dari proses pelayanan. Semakin baik
mutu pelayanan akan menghasilkan pelanggan yang semakin sulit untuk dipuaskan,
karena tuntutannya juga semakin tinggi, kebutuhannya juga semakin meluas dan
beragam, maka sebagai pemberi jasa harus mengadakan perbaikan terus menerus.
5. Memberdayakan
pelanggan
Menawarkan jenis-jenis layanan yang
dapat digunakan sebagai sumberdaya atau perangkat tambahan oleh pelanggan untuk
menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari.
BAB
3
PEMBAHASAN
3.1 Sistem Pelayanan Kesehatan
Indonesia
Sistem pelayanan kesehatan di indonesia meliputi
pelayanan rujukan yang berupa:
1. Pelayanan
kesehatan dasar
Pada umumnya pelayanan
dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan
Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.
2. Pelayanan
kesehatan rujukan
Pada umumnya dilaksanakan di rumah
sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar
maupun pelayanan kesehatan rujukan.
3.1.1 Sistem
Rujukan (Referal System)
Di negara Indonesia sistem rujukan telah
dirumuskan dalam SK. Menteri Kesehatan RI No.32 tahun 1972, yaitu suatu sistem
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab
timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara
vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih
mampu atau secara horizontal dalam arti antara unit-unit yang setingkat
kemampuannya. Macam rujukan yang berlaku di negara Indonesia telah ditentukan
atas dua macam dalam Sistem Kesehatan Nasional, yaitu:
1) Rujukan
kesehatan
Rujukan kesehatan pada
dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat (public health services). Rujukan ini dikaitkan dengan upaya
pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Macamnya ada tiga,
yaitu: rujukan teknologi, rujukan sarana, dan rujukan operasional.
2) Rujukan
medis
Pada dasarnya berlaku
untuk pelayanan kedokteran (medical
services). Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit.
Macamnya ada tiga, yaitu: rujukan penderita, rujukan pengetahuan, rujukan
bahan-bahan pemeriksaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.3.

Gambar 3.1 rujukan pelayanan kesehatan
Manfaat
sistem rujukan, ditinjau dari unsur pembentuk pelayanan kesehatan:
1. Dari
sudut pemerintah sebagai penentu kebijakan (policy
maker)
a. Membantu
penghematan dana, karena tidak perlu menyediakan berbagai macam peralatan
kedokteran pada setiap sarana kesehatan.
b. Memperjelas
sistem pelayanan kesehatan, karena terdapat hubungan kerja antara berbagai
sarana kesehatan yang tersedia.
c. Memudahkan
pekerjaan administrasi, terutama pada aspek perencanaan.
2. Dari
sudut masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan (health consumer)
a. Meringankan
biaya pengobatan, karena dapat dihindari pemeriksaan yang sama secara
berulang-ulang.
b. Mempermudah
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, karena telah diketahui dengan jelas
fungsi dan wewenang setiap sarana pelayanan kesehatan.
3. Dari
sudut kalangan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan keseahatan (health provider)
a. Memperjelas
jenjang karier tenaga kesehatan dengan berbagai akibat positif lainnya seperti
semangat kerja, ketekunan, dan dedikasi.
b. Membantu
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, yaitu: kerja sama yang terjalin.
c. Memudahkan
atau meringankan beban tugas, karena setiap sarana kesehatan mempunyai tugas
dan kewajiban tertentu.
3.1.2 Masalah
Pelayanan Kesehatan
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi, terjadi beberapa perubahan dalam pelayanan kesehatan. Disatu pihak
memang mendatangkan banyak keuntungan, yaitu meningkatnya mutu pelayanan yang
dapat dilihat dari indikator menurunnya angka kesakitan, kecacatan, kematian
serta meningkatnya usia harapan hidup rata-rata. Namun dipihak lain, perubahan
tersebut juga mendatangkan banyak permasalahan diantaranya:
1. Fragmented health services (terkotak-kotaknya
pelayanan kesehatan).
Timbulnya perkotakan
dalam pelayanan kesehatan erat hubungannya dengan munculnya spesialis dan
subspesialis dalam pelayanan kesehatan. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah
menyulitkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang apabila
berkelanjutan, pada gilirannya akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
2. Berubahnya
sifat pelayanan kesehatan
Muncul akibat pelayanan
kesehatan yang terkotak-kotak, yang pengaruhnya terutama ditemukan pada
hubungan dokter dengan klien. Sebagai akibatnya, munculnya spesialis dan
subspesialis menyebabkan perhatian penyelenggara pelayanan kesehatan tidak
dapat lagi diberikan secara menyeluruh. Perhatian tersebut hanya tertuju pada
keluhan ataupun organ tubuh yang sakit saja.
Perubahan
sifat pelayanan kesehatan makin bertambah nyata, tatkala diketahui pada saat
ini telah banyak dipergunakan berbagai alat kedokteran yang canggih,
ketergantungan yang kemudian muncul terhadap berbagai peralatan tersebut,
sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan, diantaranya:
1. Makin
regangnya hubungan antara petugas kesehatan (tenaga medis, paramedis, dan
klien) telah terjadi tabir pemisah antara dokter juga perawat dengan klien
akibat dari berbagai peralatan kedokteran yang dipergunakan.
2. Makin
mahalnya biaya kesehatan. Kondisi seperti ini tentu mudah diperkirakan akan
menyulitkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.
3.1.3 Stratifikasi
Pelayanan Kesehatan
Pada dasarnya, ada tiga macam srata
pelayanan kesehatan di semua negara, yaitu:
1. Primary health services (pelayanan
kesehatan tingkat pertama)
Merupakan pelayanan
kesehatan yang bersifat pokok atau basic
health services, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat
serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Umumnya bersifat rawat jalan (ambulatory/out
patient services).
2. Secondary health services (pelayanan
kesehatan tingkat kedua)
Pelayanan kesehatan
lebih lanjut, bersifat rawat inap (in
patient services), dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan
tersedianya tenaga-tenaga spesialis.
3. Tertiary health services (pelayanan
kesehatan tingkat ketiga)
Pelayanan kesehatan yang bersifat
lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis.
3.1.4 Faktor-faktor
yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan
1. Pergeseran
masyarakat dan konsumen
Hal ini sebagai akibat
dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap peningkatan
kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya pengobatan. Sebagai masyarakat yang
memiliki pengetahuan tentang masalah kesehatan yang meningkat, maka mereka
mempunyai kesadaran lebih besar yang berdampak pada gaya hidup terhadap
kesehatan. Akibatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan meningkat.
2. Ilmu
pengetahuan dan teknologi baru
Pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi disisi lain dapat meningkatkan pelayanan kesehatan
karena adanya peralatan kedokteran yang lebih canggih dan memadai, namun disisi
lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada beberapa hal,
diantaranya adalah:
a. Dibutuhkan
tenaga kesehatan profesional akibat pengetahuan dan peralatan yang lebih
canggih dan modern.
b. Melambungnya
biaya kesehatan
c. Meningkatnya
biaya pelayanan kesehatan
3. Isu
legal dan etik
Sebagai masyarakat yang
sadar terhadap haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan, isu
etik dan hukum semakin meningkat ketika mereka menerima pelayanan kesehatan.
Disatu pihak, petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kurang seksama akibat
meningkatnya jumlah konsumen, disisi lain konsumen memiliki pengertian yang
lebih baik mengenai masalah kesehatannya. Pemberian pelayanan kesehatan yang
kurang memuaskan dan kurang manusiawi atau tidak sesuai harapan, maka persoalan
atau dilema hukum dan etik akan semakin meningkat.
4. Ekonomi
Pelayanan kesehatan
yang sesuai dengan harapan barangkali hanya dapat dirasakan oleh orang-orang
tertentu yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh fasilitas pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan, namun bagi klien dengan status ekonomi yang rendah
tidak akan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, karena tidak
mampu menjangkau biaya pelayanan kesehatan. Akibatnya masyarakat enggan untuk
mencari diagnosis dan pengobatan. Penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan
menurun akibat biaya pelayanan yang tinggi dan tidak adanya jaminan bagi
masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.
5. Politik
Kebijakan pemerintah dalam sistem
pelayanan kesehatan akan berpengaruh pada kebijakan tentang bagaimana pelayanan
kesehatan yang diberikan dan siapa yang menanggung biaya pelayanan kesehatan.
Tentunya saat ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang kurang mampu dengan
adanya kebijakan di tiap-tiap kabupaten tentang pengobatan gratis di pusat
pelayanan kesehatan masyarakat. Namun demikian, jangan sampai kebijakan
pengobatan gratis tersebut akan mengurangi mutu dari pelayanan kesehatan yang
ujung-ujungnya karena tidak mendapat keuntungan dari program tersebut.
3.2 Konsep Indonesia Sehat 2010
3.2.1 Perilisan Sehat 2010 di dunia
Pada bulan
Januari 2000, Rakyat Sehat 2010 dirilis, tujuan untuk dekade ini bahkan lebih
ambisius daripada dekade sebelumnya. Sebagai contoh, bukan bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan kesehatan saja, seperti tujuan untuk tahun 2000, Rakyat Sehat 2010
bertujuan untuk menghilangkan kesehatan kesenjangan.
Tujuan fokus
pada dua tujuan menyeluruh
·
Semua bantuan dari Amerika meningkatkan usia
harapan hidup dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka.
·
Menghilangkan
kesenjangan kesehatan yang ada antara segmen yang berbeda dari penduduk AS.
Bidang-bidang tertentu yang menjadi perhatian untuk masing-masing tujuan adalah
sebagai berikut:
·
Promosi
kesehatan: Nutrisi, aktivitas fisik dan kebugaran, konsumsi tembakau, alkohol,
dan obat-obatan lainnya, keluarga berencana,
perilaku kasar, kesehatan mental, dan program-program
berbasis pendidikan dan masyarakat.
·
Perlindungan
Kesehatan: Kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan, kecelakaan,
keamanan makanan dan obat-obatan, dan kesehatan mulut.
·
Pencegahan
layanan prioritas: kesehatan ibu dan bayi, imunisasi dan penyakit menular,
Human Immunodeficiency Virus (HIV) infeksi, penyakit menular seksual, penyakit
jantung dan stroke, kanker, diabetes dan gangguan menonaktifkan kronis, dan
layanan pencegahan klinis untuk ini; dan mental dan gangguan perilaku.
·
Prioritas
perbaikan Sistem: Pendidikan kesehatan dan layanan pencegahan, dan sistem
surveilans dan data (USDHHS, 2000c)
3.2.2 Konsep
Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Tujuan utama pembangunan masional adalah
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan
visi pembangunan nasional melalui pembangunan kesehatan yang ingin dicapai
untuk mewujudkan Indonesia sehat 2010. Pernyataan tersebut di atas sesuai
dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945
alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan
program Pembangunan Nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang optimal.
Untuk menjawab tantangan pembangunan
kesehatan yang berkelanjutan termasuk konsistensi, kebijakan, keterlibatan
lintas sector serta berdasarkan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat yang
mutakhir, dirumuskanlah paradigma sehat yang merupakan upaya untuk lebih
meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Adapun rumusan paradigma
sehat tersebut telah tertuang di dalam visi :Indonesia Sehat 2010”. Visi yang
tertuang dalam paradigma sehat adalah visi jangka menengah, tentu saja bila
visi jangka menengah itu telah tercapai, akan ditindak lanjuti dengan visi
jangka menengah selanjutnya, yang kualitas indikatornya lebih tinggi. Begitu
seterusnya sehingga pembangunan kesehatan bisa berkelanjutan dan konsisten
untuk menciptakan Indonesia Sehat.
Pada tahun 1948 WHO menyepakati antara
lain bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak yang
fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin,
politik yang dianut dan social ekonominya. Kemudian pada tahun 1980, WHO
mendeklarasikan “Health For All By The
Year 2000” yang isinya menghimbau kepada anggota WHO supaya melakukan
langkah-langkah dalam melakukan pembangunan kesehatan sehingga derajat kesehatan
setiap orang meningkat.
Negara Indonesia menindaklanjuti
komitmen ini melalui Sistem Kesehatan Nasional atau yang dikenal dengan
singkatan SKN tahun 1982 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang
Kesehatan (RPJPK). Selanjutnya memasuki abad ke-21 Indonesia telah menetapkan
“Indonesia Sehat 2010” sebagai visi pembangunan kesehatan. Penerapan paradigma
baru pembangunan kesehatan baru, yaitu paradigma sehat merupakan upaya untuk
lebih meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Dalam mewujudkan
visi, ditetapkan misi pembangunan kesehatan. Menyongsong abad ke-21, secara
nasional telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun1999 tentang Pemerintah
Daerah sebagai suatu kebijakan baru otonomi pembangunan dengan basis wilayah
kabupaten atau kota, sehingga diperlukan suatu strategi pembangunan wilayah
dengan prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.
Dengan keanekaragaman tingkat
perkembangan social, ekonomi dan budaya masyarakat berbagai daerah Indonesia,
maka perlu ditetapkan indikator-indikator untuk masing-masing daerah selain
yang bersifat nasional. Penajaman sasaran dan prioritas secara lebih spesifik,
perlu dirumuskan oleh masing-masing daerah. Adanya perubahan-perubahan baik
dalam lingkungan global, nasional, maupun yang spesifik di masing-masing daerah
dan kecenderungannya serta masih adanya kesenjangan-kesenjangan dalam derajat
kesehatan masyarakat antar daerah, maka kebijaksanaan pembangunan kesehatan
dalam periode decade mendatang, telah dipikirkan secara cermat dan komprehensif.
Gambaran masyarakat Indonesia di masa
depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyakat, bangsa
dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan
perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Gambaran keadaan
masyarakat Indonesia dimasa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan
kesehatan tersebut dirumuskan sebagai “Indonesia Sehat 2010”.
Salah satu kunci keberhasilan
pembangunan kesehatan adalah mengaktualisasikan Paradigma Sehat sebagai gerakan
nasional, dimana sebagai langkah awal telah dicanangkan oleh Presiden. Paradigma
Sehat secara makro berarti bahwa pembangunan semua sector harus memperhatikan
dampaknya terhadap kesehatan, paling tidak harus memberikan kontribusi positif
bagi pengembangan perilaku dan lingkungan sehat. Sedangkan secara mikro berarti
bahwa pembangunan kesehatan akan menekan upaya promotif dan preventif
dengan tidak mengesampingkan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitative.
3.2.3 Visi
dan Misi Indonesia Sehat 2010
a. Visi
Visi
pembangunan kesehatan di Indonesia adalah : Indonesia Sehat 2010. Dalam
Indonesia Sehat 2010 dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Lingkungan
yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu:
·
Lingkungan yang bebas dari polusi
·
Tersedianya sumber air yang bersih
·
Sanitasi lingkungan yang memadai
·
Perumahan dan pemukiman yang sehat
·
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang
saling tolong menolong dengan memelihara nila-nilai budaya bangsa.
2) Perilaku
masyarakat Indonesia Sehat 2010 yang diharapkan adalah:
·
Yang bersifat proaktif untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan
·
Mencegah resiko terjadinya penyakit
·
Melindungi diri dari ancaman sakit
·
Berpartisipasi aktif dalam gerakan
kesehatan masyarakat.
3) Kemampuan
masyarakat yang diharapkan pada masa depan mampu menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non
ekonomi. Pelayanan kesehatan yang bermutu yang dimaksudkan disini adalah
pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan pemakai jasa serta diselenggarakan
sesuai standart dan etika profesi.
4) Derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republic Indonesia.
Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan
dan perilaku hidup sehat serta kemampuan masyarakat tersebut diatas, dapat
mencapai misi Indonesia Sehat.
b. Misi
Untuk
mencapai visi tersebut diatas disusunlah misi pembangunan kesehatan sebagai berikut:
1. Menggerakkan pembangunan nasional
berwawasan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan
tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sector kesehatan, tetapi sangat
dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif berbagai sector pembangunan
lainnya. Dengan demikian mewujudkan Indonesia Sehat 2010, para penanggung jawab
program pembangunan harus memasukkan pertimbangan kesehatan dalam semua
kebijakan pembangunannya. Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif
terhadap kesehatan, seyogyanya tidak diselenggarakan.
2.
Mendorong
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Kesehatan
adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, swasta dan
pemerintah. Adapun peran yang dimainkan oleh pemerintah tanpa kesadaran
individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, maka
tujuan Indonesia Sehat tidak akan tercapai. Perilaku sehat dan kemampuan
masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
sangat menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan.
3.
Memelihara
dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
Salah
satu tanggung jawab sector kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Namun penyelenggaraan
pelayanan kesehatan tidak semata-mata
berada di tangan pemerintah, melainkan mengikutseratakan sebesar-besarnya peran
serta aktif segenap anggota masyarakat dan berbagai potensi peran swasta.
4.
Memelihara
dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta
lingkungannya.
Tugas
utama sector kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan segenap
warga negaranya, yakni setiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia,
tanpa meninggalkan upaya penyembuhan penyakit (Curative Health) dan atau pemulihan kesehatan (Rehabilitatif Health). Untuk terselenggaranya tugas tersebut, maka
penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat
promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitative.
Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat diperlukan pula terciptanya lingkungan yang sehat. Oleh karenanya
tugas-tugas penyehatan lingkungan harus pula diprioritaskan.
3.2.4 Faktor-Faktor
Penyebab Terjadinya Masalah-Masalah Kesehatan Masyarakat di Indonesia
1. Factor
Lingkungan
Yang
sering menjadi penyebab masalah dalam masyarakat adalah:
·
Kurangnya peran serta masyarakat dalam
mengatasi kesehatan
·
Kurangnya sebagaian besar rasa tanggung
jawab masyarakat dalam bidang kesehatan
2. Fartor
Perilaku dan Gaya Hidup Masyarakat
·
Masih banyaknya insiden kebiasaan
masyarakat yang dapat merugikan kesehatan
·
Adat istiadat yang kurang bahkan tidak
menunjang kesehatan
3. Factor
Sosial Ekonomi
·
Tingkat pendidikan massyarakat di
Indonesia sebagian besar masih rendah
·
Kurangnya kesadaran dalam memelihara
kesehatan
·
Tingkat social ekonomi dalam hal ini
penghasilan sebagian masih rendah
·
Kemiskinan. Mayoritas masyarakt
Indonesia masih tergolong miskin karena GNP perkapita hanya bisa disejajarkan
dengan Vietnam (Wahid & Nurul,2009)
4. Factor
Sistem Pelayanan Kesehatan
·
Cakupan pelayanan kesehatan belum
menyeluruh
·
Upaya pelayanan kesehatan sebagian besar
berorientasi pada upaya kuratif
·
Sarana dan prasarana belum dapat
menunjang pelayanan kesehatan.
3.2.5
Kebijakan pembangunan kesehatan yang
diambil pemerintah untuk mencapai Indonesia sehat 2010
Kebijakan yang ditetapkan pemerintah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat
2010, yaitu:
1. Pemantapan
kerja sama lintas sector
Penyelenggaraan
kerja sama sector harus mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
Kerja sama lintas sector merupakan hal yang utama dan perlu digalang serta
dimantapkan secara bersama untuk mengoptimalkan hasil pembangunan berwawasan
kesehatan.
2. Peningkatan
perilaku, kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta.
Perilaku
hidup sehat masyarakat sejak usia dini ditingkatkan kemitraan swasta dalam
pembangunan kesehatan dihubungkan dengan memberikan kemudahan. Peran organisasi
profesi perlu ditingkatkan terutama yang menyangkut standart dan kode etik
profesi, aktif mengembangkan IPTEK.
3. Peningkatkan
upaya kesehatan
Peningkatan
upaya kesehatan diprioritaskan pada penanganan dampak krisis ekonomi dan
peningkatan produktivitas kerja. Upaya kesalahan sector pemerintahan diarahkan
pada pelayanan kesehatan yang berdampak luas, sedangkan upaya penyembuhan dan
pemulihan penyakit dilakukan oleh swasta, pemerataan dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan ditingkatkan.
4. Peningkatan
sumber daya kesehatan
Pengembangan
tenaga kesehatan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil
sesuai dengan perkembangan IPTEK. Pengembangan tenaga ditujukan untuk
memberdayakan baik masyarakat maupun pemerintah. JPKM dan asuransi kesehatan
terus dikembangkan. Efisiensi produksi dan distribusi serta untuk obat terus
ditingkatkan, termasuk obat tradisional dan makanan minuman.
5. Peningkatan
kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
dan
manajemen KSLS ditingkatkan.
Reorganisasi,
refungsionalisasi seiring dengan desentralisasi atas dasar prinsip ekonomi.
Peningkatan pendanaan untuk berbagai upaya menejemen baik dari APBN maupun APBD
6. Peningkatan
perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, makanan
dan obat kesehatan yang tidak absah/legal
Pencegahan
produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat/manfaat dan keamanan serta
memperluas jangkauan pengawasan. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap
penyalagunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
Pemerataan dan ketersediaan obat yang terjangkau dan peningkatan pemanfaatan
obat generic.
7. Peningkatan
IPTEK kesehatan
Litbang
baru dibidang kesehatan terus dikembangkan untuk membantu memecahkan masalah
dan kendala pelasanaan program kesehatan.
3.2.6 Strategi
dan Program Pemnbangunan Kesehatan di Indonesia
Strategi pembangunan kesehatan untuk
mewujudkan Indonesia Sehat 2010 adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan
Nasional Berwawasan Kesehatan
Semua
kebijakan pembangunan nasional yang sedang dan akan diselenggarakan harus memiliki
wawasan kesehatan, artinya : program pembangunan nasional harus memberikan
kontribusi yang positif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terdapat 2 (dua)
hal, yaitu:
1) Pembentukan
lingkungan sehat
2) Pembentukan
perilaku sehat
Untuk
terselenggarakannya pembangunan berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan
kegiatan: sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga semua pihak
terkait memahami dan mampu melaksanakan pembangunan berwawasan nasional.
2. Profesionalisme
Profesionalisme
dilaksanakan melalui penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
melalui penerapan nilai-nilai normal dan etika. Untuk terselenggaranya
pelayanan yang bermutu, perlu didukung oleh penerapan berbagai kemajuan ilmu
dan teknologi kedokteran dan keperawatan. Pengembangan sumber daya manusia
mempunyai peranan penting. Pelayanan kesehatan professional tidak akan terwujud
apabila tidak didukung oleh tenaga pelaksana yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta
didukung oleh penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Semua
tenaga kesehatan dituntut untuk menunjang tinggi sumpah dan kode etik profesi.
Untuk terselenggaranya strategi profesionalisme akan dilaksanakan penentuan
standart kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasarkan kompetensi,
akreditasi dan legislasi tenaga kesehatan serta kegiatan peningkatan kualitas
sector lainnya.
3. Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
Untuk
memanfaatkan kemandirian masyarakat dalam pola hidup sehat, perlu digalang
peran serta masyarakat seluas-luasnya termasuk dalam pembiayaan, JPKM yang pada
dasarnya merupakan penataan subsistem pembiayaan kesehatan dalam bentuk
mobilisasi sumber dana masyarakat adalah wujud nyata dari peran serta
masyarakat tersebut, yang apabila berhasil dilaksanakan akan mempunyai peranan
yang besar pula dalam mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan. Untuk terselenggaranya strategi ini dengan baik akan dilaksanakan
sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan untuk semua pihak yang terkait
sehingga konsep dan program JPKM dapat dipahami. Selain itu akan dikembangkan
peraturan perundang-undangan, pelatihan Badan Pelaksana JPKM dan pengembangan
unit pembina JPKM.
4. Desentralisasi
Untuk
keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan
harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik daerah. Desentralisasi yang
inti adalah pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah
untuk mengatur system pemerintahan dan rumah tangga sendiri. Untuk
terselenggaranya desentralisasi akan dilakukan kegiatan analisa dan penentuan
pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kesehatan, penentuan upaya kesehatan
yang wajib dilaksanakan oleh daearah, pelatihan, penempatan kembali tenaga dan
lain-lain agar kegiatan strategi desentralisasi dapat terlaksana secara nyata.
3.2.7 Pilar
Indonesia Sehat 2010
Guna menunjang terwujudnya Indonesia
Sehat 2010 diperlukan 3 pilar sebagai berikut :
1. Lingkungan
Sehat
Yang
dimaksud adalah lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat yaitu : bebas polusi, tersedianya air bersih,
lingkungan memadai, perumahan pemukiman sehat, terwujudnya kehidupan yang
saling tolong-menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
2. Perilaku
Sehat
Adalah
perilaku yang proaktif memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri
dari ancaman penyakit dan berperan aktif dalam gerakan kesehatan.
3. Pelayanan
Kesehatan
Adalah
pelayanan kesehatan yang bermutu, adil
dan merata yang menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan
ekonomi dan non ekonomi, sesuai dengan standart dan etika profesi
yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta memberi kepuasan kepada
pengguna jasa.
3.3 Sistem Kesehatan Nasional
3.3.1 Pengertian
SKN
SKN
adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu
dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD
1945.
Dari
rumusan pengertian di atas, jelaslah SKN tidak hanya menghimpun upaya sektor
kesehatan saja melainkan juga upaya dari berbagai sektor lainnya termasuk
masyarakat dan swasta. Sesungguhnyalah keberhasilan pembangunan kesehatan tidak
ditentukan hanya oleh sektor kesehatan saja. Dengan demikian, pada hakikatnya
SKN adalah juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam
satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.
3.3.2 Landasan
SKN
SKN
yang merupakan wujud dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah
bagian dari Pembangunan Nasional. Dengan demikian landasan SKN adalah sama
dengan landasan Pembangunan Nasional. Secara lebih spesifik landasan tersebut
adalah:
1) Landasan
idiil yaitu Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
2) Landasan
konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya:
Ø Pasal
28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
Ø Pasal
28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang.
Ø Pasal
28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan demi kesejahteraan umat manusia.
Ø Pasal
28 H ayat (1); setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.
Ø Pasal
34 ayat (2); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3.3.3 Prinsip
Dasar SKN
Prinsip
dasar SKN adalah norma, nilai dan aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan
budaya Bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai acuan berfikir dan bertindak
dalam penyelenggaraan SKN. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:
1) Perikemanusiaan
Penyelenggaraan SKN
berdasarkan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan
dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip
kemanusiaan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak diskriminatif serta selalu
menerapkan prinsip-prinsip perikemanusiaan dalam menyelenggarakan upaya
kesehatan.
2) Hak
Asasi Manusia
Penyelenggaraan SKN
berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Diperolehnya derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa
membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Setiap anak berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3) Adil
dan Merata
Penyelenggaraan SKN
berdasarkan pada prinsip adil dan merata. Dalam upaya mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang
bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata,
baik geografis maupun ekonomis.
4) Pemberdayaan
dan Kemandirian Masyarakat
Penyelenggaraan SKN
berdasarkan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Setiap orang
dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung-jawab
untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga,
masyarakat beserta lingkungannya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus
berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta
kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial dan gotong royong.
5) Kemitraan
Penyelenggaraan SKN
berdasarkan pada prinsip kemitraan. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan
dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan
masyarakat termasuk swasta, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki.
Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat termasuk swasta serta kerjasama
lintas sektor dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam suatu jejaring yang
berhasil-guna dan berdaya-guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap
dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
6) Pengutamaan
dan Manfaat
Penyelenggaraan SKN
berdasarkan pada prinsip pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan
diselenggarakan dengan lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada
kepentingan perorangan maupun golongan. Upaya kesehatan yang bermutu
dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus
lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara berhasil-guna dan berdayaguna,
dengan mengutamakan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi agar
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan
masyarakat beserta lingkungannya.
7) Tata
kepemerintahan yang baik
Pembangunan kesehatan
diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparent),
rasional/profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat (accountable).
3.3.4 Tujuan
SKN
Tujuan
SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa,
baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil-guna dan
berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
3.3.5 Kedudukan
SKN
1) Suprasistem
SKN
Suprasistem SKN adalah
Sistem Penyelenggaraan Negara. SKN bersama dengan berbagai subsistem lain,
diarahkan untuk mencapai Tujuan Bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2) Kedudukan
SKN terhadap sistem nasional lain
Terwujudnya keadaan sehat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab
sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor lain
terkait yang terwujud dengan berbagai sistem nasional tersebut, seperti:
·
Sistem Pendidikan Nasional,
·
Sistem Perekonomian Nasional
·
Sistem Ketahanan Pangan Nasional
·
Sistem Hankamnas, dan
·
Sistem-sistem nasional lainnya
Dalam
keterkaitan dan interaksinya, SKN harus dapat mendorong kebijakan dan upaya
dari berbagai sistem nasional sehingga berwawasan kesehatan. Dalam arti
sistem-sistem nasional tersebut berkontribusi positip terhadap keberhasilan
pembangunan kesehatan.
3) Kedudukan
SKN terhadap Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
Untuk menjamin
keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan Sistem Kesehatan
Daerah (SKD). Dalam kaitan ini kedudukan SKN merupakan suprasistem dari SKD.
SKD menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya kesehatan, pembiayaan
kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan perbekalan
kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan sesuai dengan
potensi dan kondisi daerah. SKD merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.
4) Kedudukan
SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta
Keberhasilan pembangunan
kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat
yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. Di pihak
lain, berbagai sistem kemasyarakatan merupakan bagian integral yang membentuk
SKN. Dalam kaitan ini SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang
dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan
sehat serta peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Sebaliknya
sistem nilai dan budaya yang hidup di masyarakat harus mendapat perhatian dalam
SKN. Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukan oleh peran aktif
swasta. Dalam kaitan ini potensi swasta merupakan bagian integral dari SKN.
Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan perlu digalang kemitraan yang setara,
terbuka dan saling menguntungkan dengan berbagai potensi swasta. SKN harus
dapat mewarnai potensi swasta sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan
nasional yang berwawasan kesehatan.
3.3.6 Subsistem
SKN
Sesuai
dengan pengertian SKN, maka subsistem pertama SKN adalah upaya kesehatan. Untuk
dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu
diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi
Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan tersebut memerlukan
dukungan dana, sumber daya manusia, sumber daya obat dan perbekalan kesehatan
sebagai masukan SKN. Dukungan dana sangat berpengaruh terhadap pembiayaan
kesehatan yang semakin penting dalam menentukan kinerja SKN. Mengingat
kompleksnya pembiayaan kesehatan, maka pembiayaan kesehatan merupakan subsistem
kedua SKN.
Sebagai
pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi dalam
jumlah, jenis dan kualitasnya sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.
Oleh karenanya sumberdaya manusia kesehatan juga sangat penting dalam
meningkatkan kinerja SKN dan merupakan subsistem ketiga dari SKN. Sumber daya
kesehatan lainnya yang penting dalam menentukan kinerja SKN adalah sumber daya
obat dan perbekalan kesehatan.
Permasalahan
obat dan perbekalan kesehatan sangat kompleks karena menyangkut aspek mutu,
harga, khasiat, keamanan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi konsumen
kesehatan. Oleh karena itu, obat dan perbekalan kesehatan merupakan subsistem
keempat dari SKN. Selanjutnya, SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang
oleh pemberdayaan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata
sebagai obyek pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subyek atau
penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Oleh karenanya pemberdayaan
masyarakat menjadi sangat penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu
dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Sehubungan dengan itu,
pemberdayaan masyarakat merupakan subsistem kelima SKN.
Untuk
menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna,
diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi,
integrasi, sinkronisasi serta penyerasian upaya kesehatan, pembiayaan
kesehatan, sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Berhasil atau
tidaknya pembangunan kesehatan ditentukan oleh manajemen kesehatan. Oleh karena
itu manajemen kesehatan merupakan subsistem keenam SKN.Dari uraian di atas,
dapat disimpulkan bahwa SKN terdiri dari enam subsistem, yakni:
·
Subsistem Upaya Kesehatan
·
Subsistem Pembiayaan Kesehatan
·
Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan
·
Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan
·
Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
·
Subsistem Manajemen Kesehatan
3.3.7 Derajat
Kesehatan Masyarakat Indonesia
Masyarakat
adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling
berinteraksi. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system
adat istiadat tertentu yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa
identitas bersama. Sehat adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi
kesejahteraan fisik, mental dan social, bukan semata-mata bebas dari penyakit
dan cacat atau kelemahan.
Ciri-ciri
masyarakat sehat:
1) Adanya
peningkatan kemampuan dari masyarakat untuk hidup sehat
2) Mampu
mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan kesehatan
(health promotion), pencegahan penyakit (health prevention), penyembuhan
(curative) dan pemulihan kesehatan (rehabilitative health) terutama untuk ibu
dan anak.
3) Berupaya
selalu meningkatkan kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi dasar
yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu
lingkungan hidup.
4) Selalu
meningkatkan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status social
ekonomi masyarakat
5) Berupaya
selalu menurunkan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan
penyakit.
a)
Indicator
Yang Berhubungan Dengan Derajat Kesehatan Masyarakat.
10
Indikator menurut Sistem Kesehatan Nasional (yang di ambil dari 12 indikator
menurut H.L.Blum)
1. Life
span
Lamanya usia harapan
untuk hidup dari masyarakat atau dapat juga di pandang sebagai derajat kematian
masyarakat yang bukan karena mati tua
2. Disease
or infirmity
Keadaan sakit atau
cacat secara fisiologis dan anatomis dari masyarakat
3. Discomfort
or illness
Keluhan sakit dari
masyarakat tentang keadaan somatic, kejiwaan, maupun social dari dirinya.
4. Disability
or incapacity
Ketidakmampuan
seseorang dalam masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan peran
sosialnya karena sakit
5. Participation
in health care
Kemampuan dan kemauan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dirinya agar selalu dalam keadaan
sehat
6. Health
behavior
Perilaku nyata dari
anggota masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan kesehatan
7. Ecologic
behavior
Perilaku masyarakat
terhadap lingkungan hidupnya terhadap spesies lain, sumber daya alam, dan
ekosistem
8. Sosial
behavior
Perilaku anggota
masyarakat terhadap sesame, keluarga, komunitas dan bangsanya.
9. Interpersonal
relationship
Kualitas komunikasi
anggota masyarakat terhadap sesamanya
10. Reserve
or positive health
Daya tahan anggota
masyarakat terhadap penyakit atau kapasitas anggota masyarakat dalam menghadapi
tekanan – tekanan somatic, kejiwaan, dan social
11. External
satisfaction
Rasa kepuasan anggota
masyarakat terhadap lingkungan sosialnya. Meliputi : rumah, sekolah, pekerjaan,
rekreasi, transportasi dan sarana pelayanan kesehatan yang ada
12. Internal
satisfaction
Kepuasan anggota
masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan dirinya sendiri
b) Indikator
derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat dilihat dari:
1. Usia
harapan hidup ( life expectiancy)
Usia harapan hidup diharapkan semakin meningkat pada tahun 1967
(45 tahun), tahun 1980 (50 tahun), tahun sekarang 2000 sekurang – kurangnya
menjadi usia 60 tahun. Sedangkan pada tahun 2001 menjadi 66,2 tahun dan tahun
2010 diharapkan menjadi 67,9 tahun
2. Angka
kematian bayi (infant mortality) dan balita menurun.
Pada tahun 1980 angka
kematian bayi sekitar 100/1.000 kelahiran hidup, di harapkan pada tahun 2000
menjadi setinggi – tingginya 45/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2001 diharapkan
menjadi turun 35/1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menurun dari
40/1.000 balita dan menjadi setinggi – tingggi 15/1.000 anak balita pada tahun
2000
3. Angka
kematian ibu melahirkan (maternal mortality rate). Angka kematian ibu
melahirkan di harapkan menurun dari 334 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup
4. Tingkat
kecerdasan penduduk.
Hal ini dapat di ukur
dengan tingkat tingkat pendidikan golongan wanita, di mana diharapkan terjadi
penurunan angka buta huruf dari sekitar 50% pada tahun 1977 menjadi sekitar 25
% pada tahun 2000
5. Bayi
lahir.
Bayi yang di lahirkan
dari ibu dengan berat badan 2500 gram atau kurang, turun menjadi setinggi –
tingginya 7 % pada tahun 2000
6. Angka
kesakitan (morbiditas)
§ Angka
kesakitan yang di sebabkan oleh kuman penyebab diare menurun dari 400/1.000
penduduk menjadi setinggi – tingginya 200/1.000 penduduk pada tahun 2000
§ Angka
kesakitan yang di sebabkan penyakit tuberculosis paru menurun dari 3/1.000
penduduk, menjadi 2/1.000 penduduk pada tahun 2000. Indonesia tahun 2008
menempati urutan ke-3 dunia untuk banyaknya kasus tuberculosis paru yang di
temukan dan urutan pertama dunia untuk angka kematian terbanyak akibat penyakit
menular
§ Angka
kesakitan penyakit tetanus neonatorum berkurang sampai 25% dari 11/1.000
kelahiran pada tahun 1980 menjadi 1/1.000 kelahiran pada tahun 2000
§ Angka
kesakitan penderita kelainan jiwa (psikosis) dapat di pertahankan ada rasio 1
-3 / 1.000 penduduk dan jumlah penderita gangguan jiwa yang relatif ringan /
neurosa dan gangguan perilaku pada rasio 20 – 60/ 1.000 penduduk
Namun, status kesehatan ini masih jauh tertinggal
apabila dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara – negara ASEAN
lainnya meskipun Indonesia telah mencanangkan berbagai komitmen global seperti
pencapaian sasaran millennium development goal pada tahun 2010.
c) Indikator
yang berhubungan dengan upaya kesehatan
1. Angka
cakupan imunisasi untuk anak – anak di bawah usia 14 bulan meningkat dari 40%
pada tahun 1980 menjadi 80% pada tahun 2000
2. Angka
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari
40% menjadi 80% pada tahun 2000
3. Angka
cakupan penyediaan air bersih meningkat dari 18% penduduk pedesaan dan 40%
penduduk kota pada tahun 1980 menjadi 100% pada tahun 2000
d) Indikator
yang menyatakan derajat kesehatan masyarakat sehat menurut WHO
1. Indikator
yang berhubungan dengan keadaan status kesehatan masyarakat, yang meliputi:
·
Indicator komprehensif, yaitu angka
kematian kasar atau CDR (Crude Date Rate) menurun, rasio angka kematian
(mortalitas) proposional menurun dan usia harapan hidup meningkat (life
expectancy rate)
·
Indicator spesifik, yaitu angka kematian
ibu dan anak menurun, angka kematian karena penyakit menular menurun serta
angka kelahiran menurun
2. Indikator
pelayanan kesehatan yang meliputi :
·
Rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah
penduduk seimbang
·
Distribusi tenaga kesehatan merata
·
Informasi lengkap tentang jumlah tempat
tidur di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain
·
Informasi tentang jumlah sarana
pelayanan kesehatan di antaranya rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin,
poliklinik dan pelayanan kesehatan lainnya
3.4 MDGs (MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS)
3.4.1 Definisi
Millennium Development Goals (MDGs) atau
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium,
adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat
Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New
York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs
adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tangga 18
September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals).
Semua negara yang hadir dalam pertemuan
tersebut berkomitment untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program
pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan
isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan
hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.
Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah
pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu :
3.4.2 MDGs
di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu dari 189
negara penandatangan Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development
Goals (MDGs). Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif
yang mesti dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan
penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Masing-masing tujuan MDGs terdiri
dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum. Hal ini berarti
Indonesia harus berusaha mencapai target-target yang telah ditentukan pada
kesepakatan tersebut pada 2015 mendatang. Untuk mencapai tujuan MDGs tahun 2015
diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan, terutama pemerintah (nasional dan lokal), kaum akademika, media,
sektor swasta, komunitas donor, dan masyarakat sipil.
1) Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim dan
Kelaparan
Pada tahun 1990, 15,1% penduduk
Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta
orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada
tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat
mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015, jika tingkat
pendapatan masyarakatnya meningkat terutama pada masyarakat miskin. Tingkat
pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan
kesempatan kerja dan pengembangan usaha.
Dalam usaha penanggulangan kemiskinan
dan pengangguran yang dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat, kebijakan pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, Strategi Nasional Penanggulangan
Kemiskinan (SNPK). Dan salah satu upaya yang ditempuh untuk menanggulangi
kemiskinan adalah usaha Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM
Mandiri).
2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Target MDGs kedua adalah mencapai
pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia,
baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan
Program Wajib Belajar 9 tahun. Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses
untuk pendidikan SD. Akan tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok
negeri yang belum dapat menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat
putus sekolah dapat mencapai 8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini
masih perlu ditingkatkan dan manajemen pendidikan juga kurang baik.
Untuk meningkatkan tingkat pendidikan di
Indonesia, pemerintah mendukung program wajib belajar 9 tahun melalui program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun 2009, dana BOS diberikan selama 12
bulan untuk periode Januari – Desember 2009 dengan total: SD/SDLB di kota
sebesar Rp.400.000,-/siswa/tahun sedangkan di kabupaten Rp.
297.000,-/siswa/tahun. Dengan program BOS, diharapkan pendidikan dasar di
Indonesia dapat terjangkau bagi semua.
3) Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan
Perempuan
Pada pasal 27 UUD 1945 telah dijamin
kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan
sehingga Indonesia telah mencapai kemajuan dalam mengatasi persoalan
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah
membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjangan dalam dunia pendidikan.
Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan, baik partisipasi bersih
maupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan
tetapi, keberhasilan ini masih perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia
yang lebih tua. Masih terdapat kesenjangan dan anggapan yang salah dalam
konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir
terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan
kesetaraan imbalan) hingga di bidang politik. Proporsi perempuan dalam
pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula dengan keterwakilan
perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%.
4) Mengurangi Tingkat Kematian Anak
Indonesia telah mencapai target yang
ditetapkan oleh MDGs ( MDGs menargetkan angka kematian bayi dan balita 65/1000
kelahiran hidup) yaitu, Angka Kematian Balita (AKBA) menurun dari 97/1000
kelahiran hidup pada tahun 1989 menjadi 46/1000 kelahiran hidup pada tahun
2000; Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 68/1000 kelahiran menjadi 35/1000
kelahiran hidup pada tahun 1999. Pada umumnya kematian bayi dan balita
disebabkan oleh infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain
penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak
(meningitis), typhus dan encephalitis juga menjadi penyebab kematian.
Indonesia sedang mencanangkan Program
Nasional Anak Indonesia yang menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai
salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak
Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,
dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil.
Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan
kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan
peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif,
bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran
yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di
masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak
dan balita karena UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap
anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial
menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka.
5) Meningkatkan Kesehatan Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari
400/100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 307/100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2000. Angka tersebut masih jauh dari target Nasional pada tahun 2015
yaitu 124/100.000 kelahiran. Penyebab kematian ibu adalah pendarahan (28% dari
total kematian ibu); ekslampia/gangguan akibat tekanan darah tinggi saat
kehamilan (13% dari total kematian ibu); partus lama dan infeksi (9% dari total
kematian ibu); aborsi yang tidak aman (11% dari total kematian ibu); sepsis,
penyebab lain kematian ibu karena kebersihan dan hygiene yang buruk pada saat
persalinan atau karena penyakit akibat hubungan seks yang tidak terobati (10%
dari total kematian ibu).
Kompikasi persalinan menurun apabila
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di lingkungan yang hygiene
dengan sarana yang memadai. Menurut data Susenas terjadi peningkatan proporsi
kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari 41% pada tahun 1990 menjadi
68% pada tahun 2003. Sedangkan target Nasional pada tahun 2010 adalah 90%. Selain
itu, angka pemakaian kotrasepsi pada pasangan usia subur juga menjadi indikator
peningkatan kesehatan ibu. Angka pemakaian kontrasepsi pada usia subur
dilaporkan meningkat dari 50% pada tahun 1990 menjadi 54% pada tahun 2002.
6) Memerangi HIV/AIDS dan penyakit
menular lainnya
Penurunan HIV/AIDS, malaria dan penyakit
menular lainnya mendapat perhatian yang besar dalam MDGs bidang kesehatan. Di
Indonesia, sampai akhir September 2003, tercatat 1239 kasus AIDS dan 2685 kasus
HIV positif. Para ahli memperkirakan hingga saat ini terdapat 90.000-130.000
orang Indonesia yang hidup dengan HIV. Pola penyebarannya lewat hunbungan
seksual dan napza suntik. Di Jakarta terjadi peningkatan infeksi HIV pada
pengguna napza suntik dari 15% pada tahun 1999 menjadi 47,9 pada 2002. Selain
itu, Di Jakarta Utara menunjukkan prevalensi HIV dikalangan ibu hamil mengalami
peningkatan dari 1,5 % pada tahun 2000 menjadi 2,7 pada tahun 2001.
Selain HIV/AIDS, Malaria juga menjadi
penyakit yang harus berantas. Hampir separuh dari penduduk Indonesia tinggal di
daerah endemic malaria. Rata-rata prevalensi malaria diperkirakan 850/100.000
penduduk, dengan angka tertinggi di Gorontalo, NTT, dan Papua. Angka kematian
spesifik karena malaria diperkirakan 10/100.000 penduduk.
Kemudian, Indonesia menempati urutan ke
tiga kasus Tuberkulosis (TB). Penyakit TB merupakan penyakit kronik, melemahkan
tubuh dan sangat menular. Penyembuhan memerlukan diagnosis akurat melalui
pemeriksaan mikroskopis, pengobatan jangka panjang dengan konsumsi obat anti Tb
yang rutin. Dilaporkan dalam 100.000 penduduk terdapat 271 yang menderita TB
dengan 122 diantaranya BTA positif. Angka Kematian Spesifik karena TB adalah
68/100.000 penduduk. Pada tahun 2001 penderita yang menyelesaikan
pengobatan lengkap dan sembuh adalah 85,7 %. Namun, kelangsungan berobat pada penderita
TB tidak hanya detentukan oleh kepatuhan berobat, tetapi juga ketersediaan obat
yang tidak teputus di fasilitas kesehatan. Survey pada tahun 2000 terhadap stok
obat anti TB di fasilitas kesehatan menunjukkan angka kehabisan stok bervariasi
antara 2-8%.
7) Memastikan Kelestarian Lingkungan
Di Indonesia ancaman terhadap hutan
hujan semakin menjadi-jadi, apalagi pada era desentralisasi dan otonomi daerah
lebih banyak lagi hutan yang dieksploitasi, pembalakan liar semakin
menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab
utamanya adalah lemahnya supremasi hukum dan kurangnya pengertian dan
pengetahuan mengenai tujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungn biosfer.
Akses dan ketersediaan informasi
mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merupakan aspek yang perlu
ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan
dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah
terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini tidak
tertutup harus diketahui juga oleh kaum bisnis dan masyarakat kota yang semakin
tidak peduli akan lingkungan. Selain itu, Kualitas air yang sampai ke
masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM sebagian ternyata tidak memenuhi
persyaratan air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Masalah
ini disebabkan oleh kualitas jaringan distribusi dan perawatan yang tidak baik
yang menyebabkan terjadinya kontaminasi. Oleh karena itu, promosi lingkungan
juga harus disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan kebersihan,
sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat
berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada.
Berdasarkan data terakhir yang tersedia,
akses masyarakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan
tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di
tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini
tampak dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi. Oleh
karena itu, kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada
pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada
masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk
meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat
di seluruh Indonesia.
8) Mengembangkan Kemitraan untuk
Pembangunan
Tujuan kedelapan berisikan aksi yang
harus dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan
1-7 MDGs. Konsensus Monterrey yang merupakan hasil dari Konferensi
Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002, dipandang
sebagai unsur kunci tujuan delapan MDGs. Konsensus tersebut berintikan
kebebasan perdagangan, aliran dana swasta, utang, mobilisasi sumberdaya
domestic dan hibah untuk pembangunan. Faktanya, investasi dalam bidang
kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting,
terutama di sektor kesehatan.
BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Sistem pelayanan kesehatan di indonesia meliputi pelayanan
rujukan. Indonesia sehat 2010 merupakan program dunia visi bangsa untuk
meningkatkan kesehatan bangsa, menyediakan kerangka kerja untuk
mengidentifikasi populasi beresiko dan untuk mengembangkan strategi pencegahan
bahwa alamat berbasis populasi kebutuhan. Sehat 2010 mengidentifikasi strategi
nasional untuk meningkatkan rentang kehidupan haelthy antara Amerika,
mengurangi kesenjangan kesehatan, mencapai acces universal terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas, memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, dan
meningkatkan ketersediaan informasi kesehatan terkait (USDHHS, 2000). Untuk
mewujudkan sehat 2010, diprogramkan juga MDGs (millennium development goals), dengan berbagai tujuan.
4.2 Saran
1. Bagi
perawat komunitas
Bagi perawat komunitas,
perlu memahami tentang konsep pelayanan kesehatan yang sesuai dengan aturan
pelayanan kesehatan sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan yang baik dan
bermutu.
2. Bagi
klien
Untuk klien serta
keluarga agar dapat secara mandiri berpartisipasi, meningkatkan dan memelihara
kesehatan dan perilaku, agar tujuan dari program pembangunan kesehatan bisa
berjalan dengan semestinya
3. Bagi
institusi pendidikan
Pendidikan terhadap pengetahuan
perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan baik secara formal dan informal
khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan komunitas, dengan harapan
institusi pendidikan mampu mengajarkan cara memberikan pelayanan asuhan
keperawatan komunitas sesuai standart asuhan keperawatan dan kode etik
DAFTAR PUSTAKA
Mubarak, Wahid Iqbal, Nurul Chayanti dan Bambang. (2009).
Ilmu Keperawatan Komunitas Konsep dan
Aplikasi. Jakarta: Salemba Medika.
Mubarak,
Wahid Iqbal. (2005).Pengantar Ilmu
Komunitas 1. Jakarta: Sagung Seto.
Departemen Kesehatan RI. (2000). Modul Indonesia Sehat 2010. Jakarta
Stone,Clemen,
Mc Guire and Elgsti. (2002).
Comprehensive Community Health Nursing. USA :Mosby.inc.
Stanhope,
Marcia, Jeanette Lancaster. (2004). Community
& Public Health Nursing. USA: Mosby,inc.